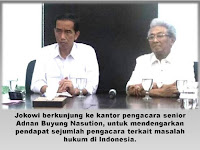Percaya gak ; ada yang baru daftar naik haji udah nyetak kartu nama dengan membubuhkan huruf H segede gajah di depan namanya. Begitu prestisius dan skaral-nya gelar HAJI bagi (sebagian besar) bangsa kita. Bahkan di beberapa daerah, gelar HAJI menjadi legiti masi untuk ber-ISTRI lebih dari SATU. Dan yang lebih menyedihkan (ma’af) tidak sedikit mereka yang dengan bangga mencantumkan dan memperkenalkan diri dengan sebutan HAJI tapi kelakuannya NOL GEDE
Selasa, 13 Oktober 2015
Jumat, 25 September 2015
Adnan Bachrum "Buyung" Nasution
 SI ABANG, ADVOKAT LOKOMOTIF DEMOKRASI ; Pengacara senior, Adnan Buyung Nasution (81), meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2015) sekitar pukul 10.15 WIB.
SI ABANG, ADVOKAT LOKOMOTIF DEMOKRASI ; Pengacara senior, Adnan Buyung Nasution (81), meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2015) sekitar pukul 10.15 WIB.Pengacara senior kelahiran 20 Juli 1934 itu sudah menderita gagal ginjal sejak Desember 2014 kemudian harus mengalami perawatan lebih lanjut setelah menjalani pencabutan gigi.Pengacara senior Adnan Buyung Nasution merupakan tokoh penting atas lahirnya Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Karakternya sangat kuat, konsistensi untuk menegakkan hukum terus dipelihara, integritas terus dipertahankannya. Buyung pun pernah membela tersangka kasus korupsi, antara lain Gayus Tambunan dan Anas Urbaningrum. Namun, keputusan Buyung membela tersangka semata untuk membela kebenaran.
Berbeda pendapat secara hukum bisa saja terjadi di tengah pandangan dan keyakinan atas kasus tertentu. Tetapi, Adnan Buyung tidak pernah dikotori oleh sikap dan perilaku koruptif.Jejak langkah Buyung telah terpatri dan tak lekang oleh zaman. Kecerdasan pendapat Buyung dan keberpihakannya pada rakyat yang dinistakan keadilannya merupakan sebagian sisi karakter yang akan terus menjadi inspirasi setiap orang. Cita-2 utamanya adalah mewujudkan negara hukum yang demokratis. Semasa hidupnya, Adnan Buyung pernah menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum (2007-2009), Ketua Umum YLBHI (1981-1983), Ketua DPP Peradin (1977), dan Direktur/Ketua Dewan Pengurus LBH (1970-1986)\
RIWAYAT SINGKAT
Prof. Dr. (lur) H. Adnan Buyung Nasution, SH atau Adnan Bahrum Nasution , lahir di Batavia (kini Jakarta), 20 Juli 1934 – meninggal di Jakarta, 23 September 2015 di Rumah Sakit Pondok Indah pada pukul 10.15 WIB karena gagal ginjal dan gangguan jantung. Beliau adalah seorang pengacara dan aktivis Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
KISAH HIDUP
Mantan jaksa yang menjadi advokat handal ini sejak kecil sudah kelihatan berbakat aktivis. Pernah menjadi anggota DPR/MPR tapi direcall. Sempat menganggur satu tahun sebelum membuka kantor pengacara (advokat) dan membentuk Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang kemudian menjadi YLBHI dan dikenal sebagai lokomotif demokrasi.
Hidupnya cukup sarat dengan tantangan. Sejak kecil, umur dua belas tahun, Buyung bersama adik satu-satunya Samsi Nasution sudah harus menjadi pedagang kali lima menjual barang loakan di Pasar Kranggan, Yogyakarta. Di pasar itu pula, ibunya, Ramlah Dougur Lubis berjualan cendol.
Sementara itu, ayahnya, R. Rachmat Nasution, bergerilya melawan Belanda dalam Clash II pada 1947-1948. "Itu masa-masa sulit. Kami hanya makan tiwul, karena tak sanggup beli nasi," katanya seperti dikutip sebuah media cetak. Sejak kecil, ia menjadikan ayahnya sebagai teladan.
"Dia pejuang, caranya pun tidak pilih-pilih. Dia bergerilya membela Republik. Sikapnya jelas, antipenjajahan dalam bentuk apa pun," ujar Buyung tentang ayahnya. Kebanggaan Buyung tentu beralasan. Ayahnya memang sosok pejuang sejati: tidak hanya berjuang lewat gerilya, tetapi juga lewat informasi.
Rahmad Nasution adalah salah seorang pendiri kantor berita Antara dan harian Kedaulatan Rakyat. Dia pula yang merintis berdirnya harian berbahasa Inggris The Time of Indonesia. "Dia menjadi semacam tokoh buat saya," kata Buyung lagi.Rupanya, Buyung juga tidak mau ketinggalan dari ayahnya dalam soal perjuangan.
Ketika SMP di Yogyakarta, ia ikut Mopel (Mobilisasi Pelajar) dan melakukan aksi protes pendirian sekolah NICA di Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978) Yogyakarta. Ia ikut merusak sekolah dan melempari guru-guru sekolah tersebut. Memang, sejak kecil, Buyung sudah kelihatan berbakat . Aktivis. Saat bersekolah di SMA Negeri I Jakarta, ia pun sudah menjadi Ketua Cabang Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI).
Kemudian, ia mengundurkan diri dan membubarkan organisasi itu karena mulai terkena bau-bau PKI dan membawa-bawa nama International Union of Student (IUS) yang kekiri-kirian. Lulus SMA, Buyung hijrah ke Bandung dan mendaftar di Institut Teknologi Bandung (ITB), jurusan Teknik Sipil. Di sana ia aktif di Perhimpunan Mahasiswa Bandung.
Tetapi ia hanya bertahan setahun di ITB, lalu pindah ke Fakultas Gabungan Hukum, Ekonomi, dan Sosial Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tidak lama di situ, pada 1957 ia pindah lagi ke Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, Universitas Indonesia, Jakarta.
Lulus sarjana muda, sambil meneruskan kuliah, ia bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Istimewa Jakarta. Meski sudah menjadi jaksa, tetapi semangatnya sebagai Aktivis tidak pudar. Ketika itu ia sempat mendirikan sekaligus menjadi Ketua Gerakan Pelaksana Ampera. Selain itu, ia juga menjadi anggota Komando Aksi Penggayangan Gestapu. Bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) ia ikut turun ke jalan sehingga diinterogasi oleh atasannya. Bahkan sempat dirumahkan selama satu setengah tahun alias diskorsing dari pekerjaannya sebagai jaksa. Ia tidak diberi pekerjaan dan tidak diberi meja di kantor. Buyung dituduh antirevolusi, anti-Manipol-Usdek.
Kemudian ia mendapat surat pindah tugas ke Manado. Lucunya, ia ditempatkan di Medan. Entah bagaimana, Buyung tidak srek dengan pemindahan itu. Akhirnya, pada 1968, Buyung meninggalkan baju jaksa. Selain itu, ia juga di-recall dari DPR/MPR. Sekitar setahun ia menganggur kemudian membentuk Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta. Untuk mendukung kerja LBH, Buyung membuka kantor pengacara (advokat). Sekali jalan, dua-duanya berkembang. Kantor pengacaranya merupakan salah satu kantor pengacara terbaik di Indonesia. Sementara itu, LBH--kemudian menjadi YLBHI dan membawahi LBH-LBH--pun tumbuh besar dan kemudian dikenal sebagai lokomotif demokrasi.
Soal pendirian LBH ini Buyung punya cerita menarik. Ketika ia menjadi jaksa dan bersidang di daerah-daerah terpencil, ia melihat orang-orang yang menjadi terdakwa pasrah saja menerima dakwaan yang ditimpakan kepadanya. Dari sana ia berpikir, orang-orang kecil yang buta hukum itu perlu dibantu. "Bagaimana kita mau menegakkan hukum dan keadilan kalau posisinya tidak seimbang. Di situ saya berpikir, harus ada orang yang membela mereka," katanya. Tetapi niat itu dipendamnya. Kemudian, saat buyung kuliah Universitas Melbourne, Australia, ia melihat bahwa di negara itu ada Lembaga Bantuan Hukum. Itu membuat ia sadar bahwa bantuan hukum itu ada pola, model, dan bentuknya. pada 1969, Buyung kembali ke Indonesia. Kemudian ia menyampaikan ide itu kepada Kepala Kejaksaan Agung Soeprapto. Soeprapto memang memuji ide itu, tetapi ia menganggap belum waktunya diwujudkan. Buyung menyadari saati itu memang belum mendukung gagasan tersebut. Ia baru bisa merealisaskani idenya membentuk LBH setelah ia keluar dari Kejaksaan.
Mula-mula gagasan itu dilontarkan kepada Profesor Sumitro dan Mochtar Lubis. Rupanya, Sumitro dan Mochtar cukup antusias mendukung ide itu. Namun, Sumitro menyarankan supaya Buyung membuka kantor advokat karena bagaimana pun Buyung harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi sebelum Sumitro sempat membantu, dia keburu diangkat sebagai Menteri perdagangan. Selanjutnya, Buyung yang izin praktek advokatnya sempat dicabut itu menemui Menteri Kehakiman Prof. Oemar Seno Adjie untuk mengkonsultasikan ide itu. Rupanya pak Menteri ini juga mendukung tapi menyarankan Buyung jadi advokat dulu supaya punya legalitas. Tanpa proses yang rumit, Buyung pun mendapatkan izin advokat, dan membuka kantor law firm. Tak lupa, ia juga mengajak beberapa temannya menjadi staf, seperti Nono Anwar Makarim, Mari'e Muhammad (bekas Menteri Keuangan).
Kantor itu kemudian berkembang.Kemudian, mulailah Buyung menyiapkan pendirian LBH. Ia mulai melakukan pendekatan dengan sejumlah advokat untuk mensosialisasi ide itu. Buyung tidak mau ada ganjalan untuk mewujudkan gagasannya. Soalnya, menurut Buyung, di beberapa negara LBH dimusuhi oleh para advokat. Tetapi syukur, ia tidak punya ganjalan apa-apa. Peserta Kongres Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), terutama Yap Thiam Hien dan Lukman Wiryadinata (bekas Menteri Kehakiman), mendukung penuh gagasan itu.
Buyung juga melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah. Ia menemui Ali Moertopo yang waktu itu menjadi asisten pribadi Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988). Presiden Soeharto dan menjelaskan ide itu seraya meminta ide itu disampaikan kepada Presiden, apakah presiden setuju atau tidak. Rupanya tak lama, ia dipanggil dan mendapat kabar bahwa Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988). Soeharto setuju dengan gagasan itu. Malah, ketika pembukaan LBH ia mendapat 10 skuter dari pemerintah.Selain pemerintah pusat, Buyung juga mendekati pemerintah daerah DKI Jakarta. Ia menemui Gubernur DKI Jakarta (1966-1977) Ali Sadikin yang waktu itu menjadi gubernur. Rupanya, Ali juga satu suara dengan yang lain. Bahkan, yang mendukung bukan Ali sebagai pribadi, tetapi pemerintah daerah DKI Jakarta. Karena dukungan-dukungan itu, kemudian lahirlah LBH tanggal 28 Oktober 1970. Buyung pun tampil sebagai pemimpin LBH pertama kali.
Namun, ada satu hal yang tidak banyak diketahui dari si Abang ini, tak lain adalah namanya. Ternyata nama Buyung sebenarnya ADNAN BAHRUM NASUTION. "Nama asli saya dalam akta kelahiran memang Adnan Bahrum Nasution," kata Buyung . Semasa kuliah, bahkan ketika menikah namanya masih tertulis Adnan Bahrum Nasution. Cuma memang ia tidak menulis lengkap namanya: Adnan Bahrum Nasution, tetapi Adnan B. Nasution.Tetapi kawan-kawannya suka memanggilnya Buyung. Perekatan nama Buyung di tengah namanya itu terjadi ketika menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1964. Waktu itu petugas administrasi disana yang kerap mendengar sapaan Buyung terhadap si Abang, langsung saja menulis lengkap nama Adnan B. Nasution sebagai Mantan Jaksa, Advokat/Konsultan Hukum, Adnan Buyung Nasution. Nama itulah yang kemudian dikenal banyak orang
KARIR
1) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum (2007-2009)
2) ketua Umum YLBHI (1981-1983)
3) Ketua DPP Peradin (1977)
4) Direktur/Ketua Dewan Pengurus LBH (1970-1986)
5) Advokat/Konsultan Hukum Adnan Buyung & Associates (1969-sekarang)
6) Anggota DPRS/MPRS (1966-1968)
7) Ketua KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) (1966)
8) Jaksa/Kepala Humas Kejaksaan Agung (1957-1968)
PENDIDIKAN
1) SMA Negeri 1 Jakarta
2) Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung
3) Fakultas Gabung Hukum, Ekonomi, dan Sosial Politik, Universitas Gadjah Mada
4) Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Indonesia
5) Studi Hukum Internasional, Universitas Melbourne, Australia
6) Universitas Utrecht, Belanda
Pesan terakhir beliau ;
"JAGALAH LBH / YLBHI, TERUSKAN PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN DAN TERTINDAS,"
demikian tulis Buyung sambil menangis sebagai pesan terakhir Buyung kepada Todung dan rekan-rekannya. Senior, rekan kerja, sahabat. Pesan Buyung itu pun memiliki makna mendalam untuk penegak hukum di Indonesia.
"Pesan bagi semuanya adalah, dia saja dalam sakitnya masih memikirkan negerinya, bangsanya (sumber Todung Mulya Lubis)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhalangan hadir melawat advokat senior Adnan Buyung Nasution. Demikian disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat bertandang ke rumah duka di Jalan Poncol Lestari Nomor 7, Lebak Bulus, Jakarta (Rabu, 23/9).
"Presiden tidak bisa melayat ke rumah duka karena beliau sedang kunker mengkoordinasi pemadaman kebakaran hutan di Kalsel, dan akan terus melanjutkan perjalanan ke Medan, ke Sinabung," jelasnya. Menurut Teten, Presiden Jokowi telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Adnan Buyung melalui pernyataan resmi. Juga mengirimkan karangan bunga.
Teten menceritakan, keduanya memiliki kedekatan secara emosional cukup dekat, lantaran Jokowi saat berkampanye di Pilpres 2014 lalu kerap bertemu pakar hukum yang juga pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tersebut. "Sehingga antara pak Presiden dengan pak Adnan Buyung punya hubungan emosional, punya kesamaan pikiran," bebernya.
Ditambahkan Teten, Presiden Jokowi juga respek dengan apa yang dilakukan Adnan Buyung dalam memajukan hak asasi manusia di Indonesia
(dihimpun dan disarikan dari berbagai sumber)
Senin, 14 September 2015
Devi Dja, Diva Pahlawati

dan kemudian menjadi Soetidjah
Dia adalah seorang penari, pemain Sandiwara dan pemain film Indonesia yang terkenal di era 1940-an. Dia tergabung pada kelompok Opera Dardanella, namun pada sekitar tahun 1940 dia hijrah ke Amerika bersama suaminya Willy Klimanoff (pendiri kelompok Dardanella). Hingga masa akhir hidupnya ia memilih berkarir di Amerika Serikat sebagai entertainer profesional dan dikuburkan di sana.
RIWAYAT HIDUP
Devi Dja memang memiliki minat seni sejak kecil, pada masa itu ia sering me- nguntit kakeknya Satiran, dan Neneknya yang bernama Sriatun, menga- men berkeliling dari kam pung keluar kampung me- metik siter. Devi Dja be- rangkat dari keluarga Jawa yang miskin di awal abad 20. Pada suatu saat, ketika mereka sedang ngamen di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, di waktu yang bersamaan kelompok Darda nella juga sedang mengadakan pertunjukan di kota tersebut. Kemudian di suatu tempat, tanpa di sengaja Piedro melihat Devi Dja sedang mengamen bersama kakek dan neneknya. Piedro mengaku tertarik dengan Soetidjah dan langsung melamarnya. Piedro tertarik pada Soetidjah ketika ia menyanyikan lagu Kopi Soesoe yang memang sedang populer ketika itu.
Meski keluarga Soetidjah keberatan, namun akhirnya Soetidjah memilih untuk menerima pinangan Pedro dan bergabung sebagai pemain pada rombongan sandiwara Dardanella. Pada awal tahun ia mulai bergabung, Soetidjah hanya dapat peran-peran kecil dan lebih sering menjadi penari yang tampil dalam pergantian antara babak. Mungkin karena Soetidjah tak penah mengenyam pendidikan sebelumnya, ia baru mulai belajar membaca dan menulis latin ketika bergabung pada kelompok Dardanella tersebut, di saat usianya 14 tahun. Dua tahun kemudian, di usianya yang ke 16, Soetidjah mulai bersinar sebagai bintang, ketika itu pemeran utama wanita Dardanella, Miss Riboet II jatuh sakit. Soetidjah pun didaulat memerankan tokoh Soekaesih, sebuah peran yang selama ini dipegang oleh Miss Riboet II dalam lakon “Dokter Syamsi”. Akting Soetidjah cukup meyakinkan, hingga kemudian ia dipanggil dengan julukan Erni oleh kawan-kawannya
KEHIDUPAN DI LUAR NEGERI
Saat Dardanella pertama kali mentas di luar negeri, Devi Dja baru 17 tahun. Dardanella adalah rombong an teater Indonesia pertama yang menyeberang ke luar negeri. Waktu berlayar ke Singapura sebelum Perang Kemerdekaan, beranggota kan 150 orang, antara lain seperti Tan Tjeng Bok, Hemy L. Duarte, Riboet II, Astaman, Subadi dan lain-lain. Jumlah yang sangat besar sekali bahkan untuk hitungan saat ini. Dardanella berkali-kali berganti nama, namun hanya Dardanella yang tetap terkenal dan menjadi buah bibir di masyarakat.
Menjelang Perang Dunia II, mereka mendarat di China dan bermain di beberapa kota. Kemudian berlayar ke India. Di Rangoon. Pada bulan Mei tahun 1937 Devi Dja menari disaksikan Jawaharlal Nehru, sebagaimana tersimpan dalam tulisan pendeknya. Melanjutkan perlawatannya ke sebelah barat, dengan jumlah anggota yang mengecil dan rontok di tengah jalan, Dardanella tampil di Turki, Paris, lalu ke Maroko dan terakhir di Jerman. Dengan kapal laut terakhir "Rotterdam" dari Belanda, mereka menuju ke Benua Amerika. Mendarat di New York dengan pemain yang tinggal beberapa saja diantaranya Ferry Kock, Eddy Kock dan lainnya. Di sini rombongan berganti nama "Devi Dja's Bali and Java Cultural Dancers", dan manggung di beberapa tempat antara lain di restoran-restoran di New York
Pengalaman Devi Dja dari Dardanella, bukan hanya pengalaman hilir mudik tampil di atas panggung di pelbagai kota di Indonesia dari bagian Barat hingga ke Timur, melainkan pengalaman hidup mereka menjadi anak panggung dan kehidupan itu sendiri.
Suatu ketika rombongan ini sedang bermain di luar negeri dan terjadi percekcokan yang akhirnya menyebabkan Devi Dja memutuskan untuk meninggalkan Dardanella dan menetap di Amerika Serikat. Hal ini justru memberikan kesempatan yang berharga, karena kontribusinya sebagai seniwati Indonesia dalam usaha-usahanya mengumpulkan dana bagi perjuangan pada masa revolusi fisik pasca kemerdekaan.
Bersama-sama dengan "The Indonesian Association" di kota San Fransisco, Devi Dja dengan grupnya, mengadakan pertunjukan seni Indonesia yang hasilnya disumbangkan kepada perjuangan RI. Setelah merasa cukup lama tinggal di Amerika mereka bermaksud kembali ke tanah air, tapi Perang Dunia II terlanjur pecah dan Indonesia diduduki oleh Jepang. Akhirnya mereka tertahan di Amerika tidak bisa pulang. Kemudian setelah PD II usai, anggota rombongan ini tinggal belasan orang, sebab sebagian berusaha pulang dan semangat pun mulai luntur.
Demi bertahan hidup di Amerika, Piedro dan Devi Dja membuka sebuah niteclub yang bernama Sarong Room di Chicago, namun sangat disayangkan niteclub tersebut terbakar habis pada tahun 1946. Piedro akhirnya merasa tak tahan dan meninggal dunia di Chicago pada tahun 1952.
Di masa awal kemerdekaan Indonesia, Devi Dja sempat bertemu Sutan Syahrir yang tengah memimpin delegasi RI untuk memperjuangkan pengakuan Internasional terhadap kemerdekaan Indonesia di markas PBB, di New York pada tahun 1947. Oleh Sutan Syahrir, dia sempat diperkenalkan sebagai duta kebudayaan Indonesia kepada masyarakat Amerika. Namanya pun makin dikenal di Amerika, oleh sebab itu tak sulit baginya mendapatkan kewarganegaraan Amerika
Pada tahun 1951 Devi resmi menjadi warga negara Amerika. Sepeninggal Piedro, Devi masih sempat mementaskan kebolehannya dari panggung ke panggung bersama anggota kelompok yang tersisa. Kemudian Devi menikah dengan seorang seniman berdarah Indian bernama Acee Blue Eagle. Namun pernikahan itu hanya berlangsung sebentar, Acce tidak suka Devi Dja bergaul dengan sesama masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika, sementara itu adalah juga dunianya. Apalagi kemudian setelah terbetik kabar, bahwa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya.
Setelah Devi bercerai, ia kemudian hijrah ke Los Angeles, kesempatan karir terbentang di sana. Devi Dja sempat menari di depan Claudette Colbert yang takjub oleh gerak tangan dan kerling mata Devi Dja.
Beberapa waktu kemudian ia menikah lagi dengan seseorang Indonesia asal Gresik yang menetap di Amerika bernama Ali Assan. Dari Ali Assan ini Devi memperoleh satu anak perempuan yang diberi nama Ratna Assan. Tapi usia pernikahan mereka pun tak lama, akhirnya mereka bercerai.
Di samping sering menggelar pertunjukan Dvi juga menyibukan diri mengajarkan tari-tarian daerah kepada penari-penari Amerika. Devi mengaku meski namanya sudah terkenal sebagai penari, tapi kehidupan kala itu sangatlah susah, mengingat dunia habis dicabik-cabik perang. Namun Devi mengaku beruntung berteman dengan para pesohor dunia sekelas Hollywood yang banyak menjadi teman akrabnya. Ia akrab dengan Greta Garbo, Carry Cooper, Bob Hope, Dorothy Lamour, dan Bing Crosby. Merekalah yang banyak membantu Devi dalam memberikan kesempatan.
Di Los Angeles Dewi juga rutin mengisi salah satu acara televisi lokal. Anaknya, Ratna Assan sempat bermain sebagai pemeran pendukung dalam film Papillon (1973) yang dibintangi Steve Mc Quin dan Dustin Hoffman. Tapi Ratna Assan kemudian tidak melanjutkan karir aktingnya di Hollywood, sesuatu yang amat disesali Devi Dja mengingat anaknya itu fasih berbahasa Inggris, tidak seperti dirinya.
Devi juga sempat bermain dalam beberapa film Hollywood, antara lain The Moon And Sixpence, yang menceritakan riwayat hidup seorang pelukis Prancis Paul Gaugin. Dia juga membintangi atau menjadi koreografer film Road to Singapore (1940), Road to Morocco (1942), The Picture of Dorian Gray (1945) di film ini, ia berperan sebagai Penari Bali, Three Came Home (1950) dan Road to Bali (1952)
Sewaktu Presiden Soekarno bersama putranya Guntur Soekarno Putra melawat ke Amerika, Devi Dja sempat menjemputnya. Oleh sebab itu saat Devi Dja mendapat kesempatan pulang ke Indonesia, ia diterima oleh Presiden Soekarno di Istana Negara. Soekarno sempat menganjurkan supaya Devi melepaskan kewarganegaraan Amerikanya, tetapi halangan besar adalah pekerjaannya. Di hati Devi Dja, tanah airnya tetaplah Indonesia, hal ini dibuktikan dengan berjuang terus memperkenalkan budaya Indonesia, dengan menari dan memperkenalkan makanan khas Indonesia.
Devi Dja pernah memimpin float Indonesia (float “Indonesian Holiday”, dengan sponsor Union Oil) dalam “Rose Parade” di Pasadena, tahun 1970. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang memimpin rombongan Indonesia yang turut serta dalam Rose Parade di Pasadena waktu itu.
Sewaktu tanda penghargaan disematkan padanya, ia memanggil putrinya: Ratna “Ini Ratna, bacalah!” Penghargaan bagi kalian, bagi kita. “Ya Mamah. Lain kali kita harus mempertunjukkan sesuatu yang lebih bagus lagi”
Devi Dja pernah tampil membela pemuda-pemuda Indonesia di pengadilan Los Angeles ketika maraknya berita tentang “Perbudakan di Los Angeles”. Devi tampil sebagai pembela pemuda-pemudi Indonesia yang dirantai dan dihadapkan ke pengadilan Amerika di Los Angeles. Namun berkat campur tangan Devi Dja bersama staf KBRI di Los Angeles, Pruistin Tines Ramadhan, dan Joop Ave, waktu itu sebagai Dirjen Protokol Konsuler di Deplu Pejambon, persoalan “budak-budak” dari Indonesia itu terselesaikan dan tidak sampai ada yang tertahan.
Di Los Angeles Devi Dja tinggal di kawasan Mission Hill, San Fernando Valley, 22 km di Utara Los Angeles. Di rumah berkamar tiga di pinggiran kota itu ia tinggal bersama putri satu-satunya, Ratna Assan. Semasa pensiun Devi Dja mendapat sedikit uang pensiun dari Union Arts, tempat dimana dia dulu bergabung.
Tahun 1982 saat berusia 68 tahun, Devi Dja pernah pulang ke Indonesia atas undangan Panitia Festival Film Indonesia. Ia sempat menjenguk teman lamanya Tan Tjeng Bok yang tergolek lemah di rumah sakit. Devi Dja kemudian meninggal di Los Angeles pada tanggal 19 Januari 1989 dan dimakamkan di Hollywood Hills, Los Angeles.
Catatan tentang Devi Dja sempat ditulis dalam beberapa buku, diantaranya Standing Ovations: Devi Dja, Woman of Java karya Leona Mayer Merrin, terbitan tahun 1989 dan dalam buku memoar mantan suaminya, "Lumhee Holot-Tee: The Art and Life of Acee Blue Eagle" karya Tamara Liegerot Elder.
(disarikan dari berbagai sumber)
Rabu, 05 Agustus 2015
Perang Bubat : Romantisme Sejarah Yang Diselewengkan
 REKAYASA SUMBER SEJARAH PERANG BUBAT ; Karya Perang Bubat yang mashur dan berdarah-darah itu hanyalah pelintiran sejarah Belanda melakukan romantisme tragis tendensius untuk membenturkan dua etnis besar Nusantara. Dan Belanda berhasil.
REKAYASA SUMBER SEJARAH PERANG BUBAT ; Karya Perang Bubat yang mashur dan berdarah-darah itu hanyalah pelintiran sejarah Belanda melakukan romantisme tragis tendensius untuk membenturkan dua etnis besar Nusantara. Dan Belanda berhasil. Berbagai bukti sejarah berhasil mengungkap kelicikan Pemerintah Kolonial Belanda dalam mendramatisir Peristiwa Sejarah Perang Bubat. Dengan dukungan penelitian ahli sejarah yang diarahkan. Pemerintah Kolonial Belanda berharap terjadi perpecahan besar di Indonesia antar dua suku utama yang ada di Indonesia.
Detil peristiwa Perang Bubat sendiri baru dipublikasikan di Belanda oleh Prof Dr. C.C. Berg pada tahun 1828 dari Kitab Kidung Sundayana (Bali) dan Kitab Kidung Sunda (Jawa Barat). Tahun publikasi penelitian ini adalah tahun ketika di Jawa Tengah sedang berkobar Perang Diponegoro (1825-1830). Sebuah upaya provokatif Kolonial Belanda untuk membendung Perang Diponegoro yang terindikasi meluas ke arah Jawa Barat. Simpati dari warga muslim Sunda untuk mendukung Pangeran Diponegoro pada saat itu sudah mulai terlihat. Dan jika dibiarkan maka perang Diponegoro akan meluas ke arah Jawa Barat, yang notabene memiliki hubungan batin agama Islam yang kuat dengan Pangeran Diponegoro.
Kidung Sunda sendiri memiliki kerangka waktu pembuatan, pada kisaran tahun 1628-1629, pada saat Sultan Agung Hanyokrokusumo sedang menghadapi pertempuran dengan VOC Belanda di Batavia. Pasukan Mataram yang hadir ke Jawa Barat dihadang oleh Belanda dengan berbagai macam cara. Diantaranya dengan kekuatan budaya Kidung Sunda, Cerita Parahiyangan, dan juga Naskah Wangsakerta. Dengan membangkitkan semangat kebencian antar etnis, Belanda berharap pasukan Mataram dapat dipukul mundur oleh kekuatan sentimen romantisme Sunda. Dalam sejarah, bentrok antara pasukan Mataram dan Sunda terjadi juga di beberapa lokasi. Pasukan Mataram sempat berperang dengan pasukan Sunda yang terinspirasi dengan kidung sedih buatan ini.
Sumber Pararaton yang dijadikan rujukan, tidak menceritakan secara detil Perang Bubat. Dalam Pararaton hanya ada informasi lokasi lapangan Bubat tanpa kisah detil pertempurannya. Banyak ahli sejarah yang mengutip penelitian C.C. Berg tanpa mempertimbangkan aspek kebenaran sejarah. Bahkan ahli sejarah dalam negeri banyak yang berhasil ditipu oleh Profesor C.C. Berg.
Kitab resmi Negarakertagama atau Desawarnana yang ditulis oleh pujangga keraton Majapahit Mpu Prapanca, tidak menceritakan Perang Bubat. Padahal banyak kisah yang jauh lebih memalukan lainnya, ditulis dalam Negarakertagama. Kekalahan Jayanegara dari Pemberontak Ra Kuti. Kisah pembunuhan Brawijaya II ditangan Ra Tancha, jauh lebih memalukan Majapahit, akan tetapi tertulis resmi dalam Negarakertagama.
STRATEGI KUDA TROYA KOLONIAL BELANDA
C.C. Berg melakukan studi dengan tujuan agitasi budaya ke etnis terbesar Nusantara, Jawa dan Sunda. Lebih dari 40 % penduduk Nusantara, adalah etnis Jawa, 20 % etnis Sunda, sedangkan sisanya 40 % merupakan campuran dari 400 etnis lain yang ada di seluruh Indonesia. Dengan membenturkan kedua suku terbesar di Indonesia ini pemerintah kolonial Belanda akan dengan mudah menguasai Nusantara.
Strategi licik Belanda ini terlihat jelas. Jika melihat waktu pembuatan kidung Sunda (di Jawa Barat) dan Sundayana (di Bali), terlihat jelas kaitan kidung ini, dengan jangkauan ekspansi penyatuan Pulau Jawa Bali yang dirancang Sultan Agung. Dengan menumbuhkan semangat anti etnis Jawa, diharap daerah kekuasaan Sultan Agung tidak meluas. Tahun pengumuman penelitian CC. Berg dilakukan pada tahun 1828, diarahkan untuk tujuan yang sama, membatasi daerah sebaran Perang Diponegoro.
Prof. Dr. Cristian Snouch Horgronye adalah contoh inspirator strategi Kuda Troya Belanda di Aceh. Berpura-pura masuk Islam dan menimba ilmu di Mekkah, Haji Snouch, membuat ratusan atau bahkan ribuan Hadits palsu. Tujuan utama Snouch, menghancurkan perjuangan rakyat Aceh dari dalam. Dari satu surau ke surau Snouch mengkampanyekan hadits palsu yang melemahkan perjuangan rakyat. Pada kisaran 1900-an pejuangan utama rakyat Aceh berhenti dengan gugurnya Teuku Umar (1899), Cut Nya’Dien (1905) dan keluarga. Akan tetapi seluruh pertempuran Aceh baru berhenti pada tahun 1942, ketika Jepang mengalahkan Belanda.
Setelah Proklamasi kemerdekaan, Westerling dengan arahan ratu Belanda, mengangkat kepercayaan kedatangan Ratu Adil. Sebuah pasukan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang didominasi oleh pasukan elit baret merah Belanda sempat membuat kocar-kacir petahanan TNI di Jakarta dan Bandung. Puluhan prajurit TNI tewas di tangan pasukan elit baret merah. Akan tetapi Ratu Adil buatan ini, berhasil dipukul mundur dan dinacurkan.
Pemerintah Kolonial Belanda, memiliki strategi yang sangat cerdik dalam menguasai Nusantara. Selain memanfaatkan strategi devide et impera yang terkenal itu, Belanda juga menggunakan strategi perang Trojan Horse yang sangat terkenal pada Yunani kuno. Kisah Romantisme tendensius Perang Bubat adalah salah satu strategi kuda troya yang digunakan oleh Belanda untuk memecah etnis Sunda Jawa.
Peristiwa silang pendapat di lapangan Bubat dipelintir dan diselewengkan untuk tujuan strategi pecah belah. Silang pendapat yang tidak pernah memakan korban jiwa, dari pihak manapun di lapangan Bubat. Dan ironisnya, Belanda berhasil menanamkan fiksi trauma ini sampai ratusan tahun kemudian. Sampai saat ini masih banyak yang percaya peristiwa pembantaian Bubat terjadi. Bahkan rasa dendam masih membara pada sebagian etnis suku Jawa dan Sunda.
Dan Kini Tinggal Kita Yang Harus Berkaca Dan Memaknai Dari Setiap Sudut Pandang Yang Berbeda Atas Kejadian Ini.
Jumat, 24 Juli 2015
Naik Haji Tempo Doeloe
 Bagi umat Islam di Indonesia, keinginan menunaikan rukun Islam ini tidak terbendung, termasuk di masa-masa penjajahan. Menunaikan ibadah haji makin besar jumlahnya, terutama sejak dibukanya Terusan Suez pada 1869 dan disusul dengan adanya kapal uap.
Bagi umat Islam di Indonesia, keinginan menunaikan rukun Islam ini tidak terbendung, termasuk di masa-masa penjajahan. Menunaikan ibadah haji makin besar jumlahnya, terutama sejak dibukanya Terusan Suez pada 1869 dan disusul dengan adanya kapal uap. Berdasarkan laporan resmi Pemerintah Hindia Belanda ; pada 1878 (dengan kapal layar) jamaah haji Indonesia sekitar 5.331 orang. Setahun kemudian (1880), menjadi 9.542 jamaah atau naik hampir dua kali lipat. Pada 1921 sebanyak 28.795 jamaah indonesia dari 60.786 jamaah seluruh dunia yang pergi menunaikan ibadah haji. Bahkan, saat resesi ekonomi pada 1928 jamaah haji Indonesia justru meningkat menjadi 28.952 dari 52.412 jamaah seluruh dunia. Masih dalam krisis ekonomi global (1931, 1932, dan 1932) jamaah haji Indonesia justru berjumlah di atas 39 ribu orang.
Untuk membuktikan pergi haji telah dilakukan selama berabad-abad lalu dapat kita lihat dari banyaknya mukimin yang menjadi syekh ketika sistem ini diberlakukan dan baru berakhir pada 1980-an. Di antara keturunan mereka ada yang memegang jabatan penting di Arab Saudi. Pada 1974, kebanyakan mereka tidak lagi pandai berbahasa Indonesia.
Ratusan tahun lalu, saat pesawat terbang belum ada, bahkan kendaraan daratpun baru berupa kuda dan onta dapat kita bayangkan betapa beratnya menunaikan ibadah haji pada jaman itu terutama bagi kaum muslimin yang bertempat tinggal jauh dari tanah suci seperti di Nusantara ini. Konon, perjalanan menuju Mekah dari daerah-daerah di Nusantara membutuhkan waktu 2 hingga 6 bulan lamanya karena perjalanan hanya dapat ditempuh dengan kapal layar.
Bayangkan berapa banyak perbekalan berupa makanan dan pakaian yang harus dipersiapkan para jemaah haji ! Itu pun belum tentu aman. Kafilah haji selalu harus waspada akan kemungkinan para bajak laut dan perompak di sepanjang perjalanan, belum lagi ancaman topan, badai dan penyakit. Tidak jarang ada jemaah haji yang urung sampai di tanah suci karena kehabisan bekal atau terkena sakit. Kebanyakan dari mereka tinggal di negara-negara tempat persinggahan kapal.. Saat bisa meninggalkan Indonesia, mereka singgah di Singapura atau Penang (Malaysia). Di tempat tersebut, umat Islam Indonesia yang ingin berhaji ini rela menjadi pekerja kasar. Ada yang menjadi tukang kebun, menggarap sawah, dan lainnya demi satu tujuan, yaitu berkunjung ke Baitullah. Oleh sebab itulah sebagaimana dikemukan diatas, karena beratnya menunaikan ibadah haji mudah dimengerti bila kaum muslimin yang telah berhasil menjalankan rukun Islam kelima ini kemudian mendapatkan kedudukan tersendiri dan begitu terhormat dalam masyarakat sekembalinya ke negeri asalnya. Merekapun kemudian mendapat gelar “Haji”, sebuah gelar yang umum disandang para hujjaj yang tinggal di negara-negara yang jauh dari Baitullah seperti Indonesia dan Malaysia, tapi gelar ini tidak populer di negara-negara Arab yang dekat dengan tanah suci.
Lebih Lanjut Baca - Sejarah Perhajian Di Nusantara, Kafilah Haji Dunia Abad Ke-13, Polemik Gelar HAJI, Asal Gelar Haji Di Indonesia
Wallahu a’lam bish-shawab
“Dan Allah Mahatahu yang benar/sebenarnya”
(dihimpun dari berbagai sumber – rully hasibuan)
Rabu, 22 Juli 2015
Perang Bubat, sebuah Kontroversi
 PERANG BUBAT ; sejarah atau rekayasa kolonial Belanda ? Sebuah kisah yang mestinya dapat dijadikan hikmah betapa jahatnya AMBISI PRIBADI PENGUASAdan KEKUASAAN dapat menyebabkan terjadinya sebuah TRAGEDI KECELAKAAN
PERANG BUBAT ; sejarah atau rekayasa kolonial Belanda ? Sebuah kisah yang mestinya dapat dijadikan hikmah betapa jahatnya AMBISI PRIBADI PENGUASAdan KEKUASAAN dapat menyebabkan terjadinya sebuah TRAGEDI KECELAKAANPOLITIK yang sangat menarik sekali untuk dibahas.
Lantas bagaimana kalau keduabelah pihak (Pihak Sunda dan Jawa) meng-klaim versi mereka sendiri-sendiri atau yang lebih serunya Bagaimana bila Karya Perang Bubat yang mashur dan berdarah-darah itu hanyalah PELINTIRAN SEJARAH oleh KOLONIAL BELANDA??? Dengan kata lain PERANG BUBAT itu sebenarnya hanyalah suatu perbedaan pendapat antara dua kerajaan pada waktu itu atau hanya perselisihan antara Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggrahan Bubat, NAMUN TIDAK SAMPAI MENIMBULKAN KORBAN JIWA.
Belanda melakukan ROMANTISME TRAGIS TENDENSIUS ini untuk MEMBENTURKAN ; MENGADU DOMBA dua etnis besar Nusantara (JAWA DAN SUNDA) agar tidak terjadi kesatuan dan persatuan Nusantara. Dan . . . . BELANDA nampaknya BERHASIL sampai sekarang dimana masih terlihat adanya RASA DENDAM yang membara pada sebagian etnis suku JAWA dan SUNDA. Sebuah tantangan bagi para sejarahwan dan juga para sineast kita untuk berani mengangkat kissah ini secara super colosal ke layar lebar dan bukan tak mungkin bila dibuat secara serius dan riset serta penelitian akurat yg mendalam dapat memenangkan penghargaan internasional, karena INTRIK-INTRIK POLITIK dan KEMANUSIAAN yang dikisahkan didalamnya, dapat ditampilkan secara utuh serta masih relevan dengan keadaan sekarang. Bagaimana suatu peristiwa sejarah dipandang dari masing-masing sudut yang bersebelahan dan dipergunakan untuk kepentingan salah satu pihak.
Inilah Kontroversi itu ;
Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 M pada abad ke-14, yaitu di masa pemerintahan raja Majapahit Hayam Wuruk. Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggrahan Bubat, yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama adalah Serat Pararaton serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali.
LATAR BELAKANG
Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Dyah Pitaloka Citraresmi dari Negeri Sunda. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya lukisan sang putri di Majapahit; yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu, bernama Sungging Prabangkara
Menurut catatan sejarah Pajajaran oleh Saleh Danasasmita serta Naskah Perang Bubat oleh Yoseph Iskandar, niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda. Raden Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit dianggap keturunan Sunda dari Dyah Lembu Tal dan suaminya yaitu Rakeyan Jayadarma, raja kerajaan Sunda. Hal ini juga tercatat dalam Pustaka Rajya Rajya i Bhumi Nusantara parwa II sarga 3 Dalam Babad Tanah Jawi, Raden Wijaya disebut pula dengan nama Jaka Susuruh dari Pajajaran
Meskipun demikian, catatan sejarah Pajajaran tersebut dianggap lemah kebenarannya, terutama karena nama Dyah Lembu Tal adalah nama laki-laki.. Alasan umum yang dapat diterima adalah Hayam Wuruk memang berniat memperistri Dyah Pitaloka dengan didorong alasan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan Negeri Sunda.
 |
| Hayam Wuruk |
Selain itu ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya, diantaranya dengan cara menguasai Kerajaan Dompu di Nusa Tenggara.
Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit, karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur dua negara tersebut. Linggabuana berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit dan diterima serta ditempatkan di Pesanggrahan Bubat. Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit. Menurut Kidung
 |
| Dyah Pitaloka |
 |
| Paduka Sri Baduga |
Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula. Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya (Bhayangkara) ke Pesanggrahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit.
Demi mempertahankan kehormatan sebagai ksatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu.. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar, melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan (Balamati) yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu.
Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Raja Sunda beserta segenap pejabat kerajaan Sunda dapat didatangkan di Majapahit dan binasa di lapangan Bubat
Tradisi menyebutkan sang Putri Dyah Pitaloka dengan hati berduka melakukan bela pati, bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya Tindakan ini mungkin diikuti oleh segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta ksatriya, tindakan bunuh diri ritual dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur. Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka, yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, penganiayaan, atau diperbudak.
AKIBAT YANG TIMBUL AKIBAT TRAGEDI PERANG BUBAT
Tradisi menyebutkan bahwa Hayam Wuruk meratapi kematian Dyah Pitaloka. Hayam Wuruk menyesalkan tindakan ini dan mengirimkan utusan (darmadyaksa) dari Bali - yang saat itu berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka - untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana (di Bali dikenal sebagai Geguritan Sunda) agar diambil hikmahnya. Raja Hayam Wuruk kemudian menikahi sepupunya sendiri, Paduka Sori.
 |
| Gajah Mada |
Tragedi ini merusak hubungan kenegaraan antar kedua negara dan terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian, hubungan Sunda-Majapahit tidak pernah pulih seperti sedia kala. Pangeran Niskalawastu Kancana — adik Putri Pitaloka yang tetap tinggal di istana Kawali dan tidak ikut ke Majapahit mengiringi keluarganya karena saat itu masih terlalu kecil — menjadi satu-satunya keturunan Raja yang masih hidup dan kemudian akan naik takhta menjadi Prabu Niskalawastu Kancana. Kebijakannya antara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua kerajaan.
Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat Negeri Sunda diberlakukan peraturan larangan estri ti luaran, yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa.
Tindakan keberanian dan keperwiraan Raja Sunda dan putri Dyah Pitaloka untuk melakukan tindakan bela pati (berani mati) dihormati dan dimuliakan oleh rakyat Sunda dan dianggap sebagai teladan. Raja Lingga Buana dijuluki "Prabu Wangi" (bahasa Sunda: raja yang harum namanya) karena kepahlawanannya membela harga diri negaranya. Keturunannya, raja-raja Sunda kemudian dijuluki Siliwangi yang berasal dari kata Silih Wangi yang berarti pengganti, pewaris atau penerus Prabu Wangi. Beberapa reaksi tersebut mencerminkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Sunda kepada Majapahit, sebuah sentimen yang kemudian berkembang menjadi semacam rasa persaingan dan permusuhan antara suku Sunda dan Jawa yang dalam beberapa hal masih tersisa hingga kini. Antara lain, tidak seperti kota-kota lain di Indonesia, di kota Bandung, ibu kota Jawa Barat sekaligus pusat budaya Sunda, tidak ditemukan jalan bernama "Gajah Mada" atau "Majapahit". Meskipun Gajah Mada dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional Indonesia, kebanyakan rakyat Sunda menganggapnya tidak pantas akibat tindakannya yang dianggap tidak terpuji dalam tragedi ini.
Hal yang menarik antara lain, meskipun Bali sering kali dianggap sebagai pewaris kebudayaan Majapahit, masyarakat Bali sepertinya cenderung berpihak kepada kerajaan Sunda dalam hal ini, seperti terbukti dalam naskah Bali Kidung Sunda. Penghormatan dan kekaguman pihak Bali atas tindakan keluarga kerajaan Sunda yang dengan gagah berani menghadapi kematian, sangat mungkin karena kesesuaiannya dengan ajaran Hindu mengenai tata perilaku dan nilai-nilai kehormatan kasta ksatriya, bahwa kematian yang utama dan sempurna bagi seorang ksatriya adalah di ujung pedang di tengah medan laga. Nilai-nilai kepahlawanan dan keberanian ini mendapatkan sandingannya dalam kebudayaan Bali, yakni tradisi puputan, pertempuran hingga mati yang dilakukan kaum prianya, disusul ritual bunuh diri yang dilakukan kaum wanitanya. Mereka memilih mati mulia daripada menyerah, tetap hidup, tetapi menanggung malu, kehinaan dan kekalahan.
Diatas adalah kissah sejarah selama ini yang kita kenal atau kalau boleh dikatakan itu adalah versi dari “PIHAK SUNDA”. Lalu bagaimana dengan versi “PIHAK JAWA” atau dalam hal ini adalah versi “GAJAHMADA” ? Inilah bagian yang menarik yang mungkin belum atau luput dari perhatian kita, namun semuanya bersumber dari beberapa kenyataan yang ada atau berdasarkan nalar manusia.
Berulangkali memang "KECELAKAAN POLITIK" ini timbul dan tenggelam mencari jatidirinya atas suatu kejadian suram di tanah WILWATIKTA. PASUNDAN BUBAT, yang tetap kelam sampai detik ini dan mungkin sampai semua pihak PUNYA KESADARAN POLITIS yang cukup guna memahaminya.
PASUNDAN BUBAT telah mengorbankan sebagai kambing hitam : MAHAPATIH AMANGKUBHUMI RI WILWATIKTA : MPU GAJAHMADA sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kejadiannya. Bagi mereka yang tahu atau anak keturunan yang mendapat ceritanya secara turun temurun, jawabannya adalah : TIDAK WALAUPUN IYA.
Seekor MACAN PELIHARAAN YANG PALING GANAS sekalipun semacam GAJAHMADA akan BERPIKIR ratusan kali kalau hendak MEMBUAT ULAH didepan tuannya (karena lokasi kejadian di lapangan Bubat yang cukup dekat dari Ibukota) yang sangat perkasa : NAWAPRABHU RI WILWATIKTA (Sembilan Raja penentu Kebijakan di WILWATIKTA). Maka LOGIKA dasarnya, tentu ada PERSETUJUAN atau PERINTAH dari beberapa Raja Penguasa Wilwatikta untuk mengambil langkah tegas itu.
KRONOLOGIS PRA-PERANG BUBAT VERSI JAWA ;
Saat semua persiapan pernikahan hendak dijalani, datang utusan dari pihak Pasundan yang menyerahkan surat kepada GAJAHMADA sebagai syarat atau mas kawin dari perkawinan itu. Ada 5 butir permintaan yang dicantumkan pada surat untuk DYAH RAJASANAGARA (HAYAMWURUK) melalui GAJAHMADA selaku pimpinan protokoler perkawinan.
KESATU : Meminta calon istri dari Tatar Pasundan diangkat menjadi Permaisuri.
KEDUA : Meminta Raja RAJASANAGARA tidak mengambil istri lagi selain DYAH PITALOKA.
KETIGA : Meminta anak keturunan hasil perkawinan keduanya baik itu lelaki ataupun perempuan menjadi pewaris sah tahta WILWATIKTA, tetapi bila tidak mempunyai keturunan sebagai pengganti Raja harus dipilih atas persetujuan Kerajaan Pasundan.
KEEMPAT : Meminta agar Kerajaan Pasundan tidak dijadikan bawahan dan mempunyai derajat yang sama tingginya dengan Kerajaan WILWATIKTA.
KEEMPAT : Meminta agar Kerajaan Pasundan tidak dijadikan bawahan dan mempunyai derajat yang sama tingginya dengan Kerajaan WILWATIKTA.
KELIMA : Meminta RANI KAHURIPAN : SRI TRIBHUWANATUNGGADEWI MAHARAJASA JAYAWISNUWARDHANI (ibu dari Raja HAYAMWURUK sekaligus Rani WILWATIKTA pendahulunya) untuk menjemput pengantin wanita dan menandatangani persetujuan tersebut diatas di tenda Kerajaan pasundan di lapangan Bubat.
Tertegun hebat sang GAJAHMADA mendapat permintaan mendesak di waktu yang mendesak pula, bergegas dibawalah surat itu kehadapan BHRE KAHURIPAN (karena ada beberapa hal menyangkut kekuasaan dan wibawa sang Rani). Merah padam wajah sang Rani membaca surat tersebut, karena semua permintaan dirasa sangatlah memberatkan pihak WILWATIKTA. Betapa tidak, ini seakan menjerat langkah kaki kebesaran WILWATIKTA dan menyandera masa depan kerajaan diatas sebuah perkawinan. Karena jauh-jauh hari sebelumnya sudah dideklarasikan kepada segenap rakyat, bahwa untuk menjaga kemurnian trah RAJASA, sang raja telah dijodohkan dengan sepupunya (anak dari adik beliau : DYAH WIYAT RAJADEWI). Dan anak keturunan dari keduanyalah yang akan dijadikan penerus tahta. Maka siapapun dan darimanapun istri2 raja lainnya selain Prameswari tadi tidak diijinkan menggugat masalah tahta seberapapun banyaknya anak hasil perkawinannya.
Tertegun hebat sang GAJAHMADA mendapat permintaan mendesak di waktu yang mendesak pula, bergegas dibawalah surat itu kehadapan BHRE KAHURIPAN (karena ada beberapa hal menyangkut kekuasaan dan wibawa sang Rani). Merah padam wajah sang Rani membaca surat tersebut, karena semua permintaan dirasa sangatlah memberatkan pihak WILWATIKTA. Betapa tidak, ini seakan menjerat langkah kaki kebesaran WILWATIKTA dan menyandera masa depan kerajaan diatas sebuah perkawinan. Karena jauh-jauh hari sebelumnya sudah dideklarasikan kepada segenap rakyat, bahwa untuk menjaga kemurnian trah RAJASA, sang raja telah dijodohkan dengan sepupunya (anak dari adik beliau : DYAH WIYAT RAJADEWI). Dan anak keturunan dari keduanyalah yang akan dijadikan penerus tahta. Maka siapapun dan darimanapun istri2 raja lainnya selain Prameswari tadi tidak diijinkan menggugat masalah tahta seberapapun banyaknya anak hasil perkawinannya.
Sedangkan untuk DYAH PITALOKA akan diperlakukan khusus karena berdarah sama dengan SANGRAMAWIJAYA, akan dianugrahi posisi pendamping Prameswari tetapi bukan Prameswari itu sendiri. Dari situ saja syarat Ke-1 sampai Ke-3 sebetulnya sudah gugur, tetapi yang KELIMA adalah yang dianggap menghina keluarga. Ini karena Rani Kahuripan yang sekaligus ibu dan bekas Rani WILWATIKTA harus datang menandatangani sebuah perjanjian yang bukan murni tanggung jawabnya, entah itu akan dijadikan jaminan atau memang bertujuan merendahkan martabat sang Rani yang dikenal sebagai penakluk nusantara (kenapa harus sang Rani, padahal ada suaminya dan GAJAHMADA yang ditunjuk resmi negara sebagai dutaparakrama).
Belum lagi bayangan kelam masa lalu, ketika ayahandanya NARARYA SANGRAMAWIJAYA di usir dari Tatar Sunda oleh kerabat istana setelah kematian ayahandanya, sehingga harus pulang bersama ibundanya ke tanah Singhasari, dan sekarang mereka mengincar tahta WILWATIKTA. Bergegas sang Rani KAHURIPAN mengganti busana, bukan busana untuk berpesta tetapi busana perang (beliau dikenal pula sebagai satu2nya Rani Rajasawangsa yang sering turun ke medan pertempuran memadamkan pemberontakan). Maklum sudah sang GAJAHMADA tentang langkah apa yang harus diambil, meminta keluarga untuk menahan sang Rani dan dia bergegas memberi hormat, menyampaikan paham akan langkah apa yang harus diambil lalu keluar berkonsolidasi dengan keamanan ibukota. GAJAHMADA sendiri yang datang ke lapangan Bubat menyampaikan seluruh penolakan Rani Kahuripan atas syarat yang diajukan.
Terkejut bukan kepalang sang DYAH PITALOKA, karena tidak ada syarat seperti itu diajukan oleh dirinya dan dalam pertemuan itu merasa marah dan malu akan perbuatan keluarganya yang mengajukan syarat berlebihan. Dia memohon maaf kepada GAJAHMADA dan memutuskan hendak pulang bersama rombongan pengiringnya dan bersumpah tidak akan menikah selamanya. Tetapi keinginan pulang dihadang oleh beberapa kerabatnya, mereka merasa sudah terlanjur basah maka semuanya harus keinginan harus dipertahankan demi kebaikan Kerajaan Pasundan.
GAJAHMADA merasa ini adalah masalah keluarga, maka dia keluar tenda sambil mengatakan SIAP MENGHANTAR DENGAN AMAN SELURUH ROMBONGAN UNTUK PULANG HINGGA MUARA SUNGAI BRANTAS. GAJAHMADA menunggu di luar tenda, sampai kemudian ada jeritan dari sang DYAH PITALOKA. Merangsek masuk sang Mahapatih tetapi telah mendapati sang calon pengantin rebah bersimbah darah tertancap pusaka perutnya, murka sang Amurwabhumi melihat kejahatan terjadi di depan matanya ..... berteriak lantang agar yang bertanggung jawab menyerahkan diri dan diadili sesuai hukum KUTARAMANAWA Dharmasastra atau memilih mati di tangannya.
Bukan jawaban baik2 yang di dapat, bahkan teriakan kalap orang2 di dalam tenda menyalahkan GAJAHMADA atas kejadian ini. Sebagian malah keluar tenda berteriak-teriak kalau sang Mahapatih telah membunuh calon pengantin perempuan. GAJAHMADA bukan anak kemarin sore yang mudah dijebak begitu saja, sejak keberangkatan dari puri kepatihan telah menyiapkan pasukan pengawal kasat mata di sekelilingnya, menyiapkan pasukan laut mengepung kapal para tamu ..... dan perhitungannya benar2 terjadi.
Tanpa menunggu komando lagi para pengawal bergegas membentuk formasi perlindungan pada sang Mahapatih, panah api dilepas kelangit memberi tanda seluruh kekuatan ibukota untuk waspada. SUNDANG MAJAPAHIT (ilmu beladiri yang menggunakan pedang dan keris, saat ini dilestarikan kaum Moro Philipina sebagai KALI MAJAPAHIT) rupanya bukan tandingan tentara Pasundan. Dalam sekejab deretan tenda telah berubah menjadi palagan dan semua kapal yang berlabuh ditenggelamkan. Sang Amurwabhumi kali ini tidak memberikan ampun kepada lawan-lawannya, semua ksatrya harus dibabat habis dan hanya menyisakan rombongan abdi kerajaan yang tidak paham ilmu berperang. Dentuman meriam kapal Majapahit menghajar semua kapal Pasundan dan menenggelamkannya. Asap hitam membumbung tinggi, nampak dari pendapa istana mengagetkan sang Raja. Itu lokasi BUBAT tempat calon istrinya berada, ketika meminta pengawal menyiapkan kuda, ibunya sudah hadir tepat di depannya mengatakan : GAJAHMADA sudah menyelesaikan semuanya.
Menyelesaikan bagaimana ??? ... tanya beliau, ibundanya menjawab : Menghantar rombongan pulang ke Pusandan, tetapi bila mereka melawan akan di bumi hanguskan. Tertegun sang Prabhunata, ibundanya menimpali : Karena mereka meminta mas kawin mahkota yang ada di kepalamu, dan saat ini GAJAHMADA sedang berjuang agar itu tetap berada di kepalamu. Tak paham juga atas perkataan ibundanya sang Nata gelisah dan tetap menyiapkan kuda hendak keluar istana, disodorkan sebuah surat berwarna biru oleh ibundanya. Setelah sejenak membaca, lemas lututnya dan ambruk di lantai istana. Beliau tahu batas-batas hukum sebuah diplomasi antar negara dan kali ini juga paham resiko yang muncul atasnya, bingung harus berbuat apa .... inginkan sang DYAH PITALOKA sekaligus inginkan sang Amurwabhumi
GAJAHMADA bukanlah sebuah pilihan. Beban berat sekonyong-konyong telah membuat rebah tak sadarkan diri dan harus sakit sampai beberapa lama kemudian. Beberapa bulan kemudian .... sidang NAWAPRABHU RI WILWATIKTA. Semua kejadian harus tunduk atas hukum dari satu perbuatan, atas banyaknya permintaan mancanegara atas keadilan peristiwa PASUNDAN BUBAT digelarlah sidang tersebut. Didepan sidang sang GAJAHMADA dengan gamblang menjelaskan kronologi peristiwa hingga selesainya. Sebagai pelaku utama bersedia menerima hukuman termasuk kalau harus mati sekalipun. Pengambilan suara senantiasa didahului oleh SAPTAPRABHU (1 Raja utama dan 6 Bhre / Raja Bawahan), tiba-tiba berdiri ibu sang Raja, Rani Kahuripan (SRI TRIBHUWANATUNGGADEWI MAHARAJASA JAYAWISNU WARDHANI) :
Cukup sudah empat melawan tiga yang tidak mengambil keputusan (abstain), kemudian semuanya keluar meninggalkan dua penentu utama PANEMBAHAN WILIS dan PANEMBAHAN PAWITRAN (PENANGGUNGAN). Ini harus diputuskan dengan bijak, tidak baik membiarkan perlakuan pembebasan hukuman karena dukungan para raja atas peristiwa ini walaupun dengan alasan yang benar. maka aku akan menjatuhkan hukuman atasnya, kata Panembahan Pawitran. Panembahan Wilis berulangkali menarik nafas panjang, kemudian berkata : seorang ksatria memang tahunya adalah perang apalagi kalau itu berkaitan erat dengan harga diri negara, rasanya hamba kurang bijak memutuskan hal ini, lebih baik paduka saja. Dan Panembahan Pawitran pun akhirnya memutuskan, bahwa alasan yang menjadi dasar tindakan dapat dibenarkan tetapi tata krama ibukota dan pemerintahan dimana seharusnya tindakan yang akan diambil harus sepengetahuan raja telah dilanggar.saya yang memerintahkan, maka sayalah yang harus dihukum disusul ayahanda Raja yang juga menjabat Bhre Tumapel (SRI KERTAWARDHANA DYAH CAKRADARA), juga bibi Raja Bhre Daha (SRI RAJADEWI MAHARAJASA): Dia berbuat karena membela keluargaku dan Trah Rajasa .... aku juga akan mengambil tanggung jawabnya, suaminya Bhre Wengker (SRI WIJAYARAJASA DYAH KUDAMERTA).
Hukuman yang dikenakan adalah pencopotan jabatan dan pengasingan yang bersangkutan ke daerah terpencil di LUMBANG (wilayah Probolinggo dekat air terjun Madakaripura) selama 1.000 hari. Keputusan dipahami semua pihak dan eksekusi dijalankan. Maka dicopotlah jabatan Sang MAHAPATIH AMURWABHUMI dari pundak GAJAHMADA dan menjalani hukuman buang, semua sedih karena harus tinggal berjauhan tidak kecuali sang Raja yang telah menganggap sang GAJAHMADA adalah ayah angkatnya. Tapi hukum tetap ditegakkan dan semua dijalankan. Tepat 1.000 hari dari masa pengasingan, atas perintah raja GAJAHMADA di jemput dengan rombongan besar di LUMBANG, jabatannya diaktifkan kembali sebagai Mahapatih Amurwabhumi dan ditugaskan pertama kali setelah kembali adalah mengawal perjalanan raja tetirah ke Lumajang sesuai yang tersurat di Lontar Desawarnana / Negarakretagama.
Jadi Siapa Yang Hendak Kita Salahkan Atas Peristiwa Ini ???,
Karena Pihak Wilwatikta Maupun Pihak Pasundan Sedang Menjalankan Masing2 Dharma Terbaiknya Bagi Kepentingan Kerajaannya.
TAPI, ini semua belum selesai, baca PERANG BUBAT : ROMANTISME SEJARAH YANG DISELEWENGKAN
Senin, 20 Juli 2015
Polemik Gelar HAJI
 Percaya gak ; ada yang baru daftar naik haji udah nyetak kartu nama dengan membubuhkan huruf H segede gajah di depan namanya. Begitu prestisius dan skaral-nya gelar HAJI bagi (sebagian besar) bangsa kita. Bahkan di beberapa daerah, gelar HAJI menjadi legitimasi untuk
Percaya gak ; ada yang baru daftar naik haji udah nyetak kartu nama dengan membubuhkan huruf H segede gajah di depan namanya. Begitu prestisius dan skaral-nya gelar HAJI bagi (sebagian besar) bangsa kita. Bahkan di beberapa daerah, gelar HAJI menjadi legitimasi untuk ber-ISTRI lebih dari SATU. Dan yang lebih menyedihkan (ma’af) tidak sedikit mereka yang dengan bangga mencantumkan dan memperkenalkan diri dengan sebutan HAJI tapi kelakuannya NOL GEDE
Hajji atau Ajji, adalah panggilan sosial tertinggi di banyak masyarakat. Panggilan itu adalah pengakuan status, yang imbalannya luar biasa: duduk di deretan depan dalam setiap acara bersama pemuka masyarakat, makan yang paling enak, selalu ditawari dan dipersilahkan untuk menambah, dan orang lain tidak boleh memulai makan sebelum para “barisan” depan ini mulai. Pemerintahan tradisional juga “segan” misalnya meminta para hajji ini untuk melakukan kerja bakti, tapi harus siap memberikan sumbangan yang lebih besar dari orang kebanyakan. Tidak heran bila menjadi haji lebih sering dijadikan target tertinggi dalam hidup melebihi keinginan memiliki sepeda motor , mobil atau rumah yang layak dan mewah
Saya dulu agak kesal ketika ada teman (alm) yang dengan lantang mengatakan bahwa “JANGAN PERNAH BER-BISNIS dengan orang yang NGAKU/NYEBUT dirinya HAJI”. Padahal temen (alm) tadi, kakeknya jaman tempo doeloe pulang pegi naik haji tidak kurang dari 20 kali. Ajaibnya lagi, Kakeknya itu marga SITOMPOEL justru yang meng- ISLAM-kan marga Sitompoel di kampungnya tempo doeloe dan kalo gak maka kampungnya juga akan menjadi basis ZENDING, sebab dikelilingi Kampung Batak yang sudah lebih dahulu digarap para Missionaris Kristiani (saya lupa kampungnya itu apa Luat Pahae, Sibolga, Adiankoting atau Sipirok, barangkali ada rekan yg bisa menambahkan disini?).
Namun melihat kenyataan yang ada dewasa ini, terpampang dengan jelas kelakuan mereka itu, apalagi mereka dari kalangan politisi dan eksekutif yang tak sesuai dengan gelar Haji yang disandangnya, mau gak mau saya juga harus mengakui apa yang diumbar teman (alm) tadi.
Adalagi bagaimana gelar Haji tsb menjadi permainan kata di daerah Jawa. Kalu ada Haji yang liwat, serentak mereka (terutama pemuda-2) mengeluarkan koor “KAPIR PAK KAJI” Ups salah . .Maksudnya sih ngomong “MAMPIR PAK HAJI”
Demikianlah padahal senyatanya ; GELAR HAJI umum digunakan sebagai tambahan di depan nama dan sering disingkat dengan "H". Dalam hal ini biasanya para Haji membubuhkan gelarnya dianggap oleh mayoritas masyarakat sebagai TAULADAN maupun CONTOH di daerah mereka. Bisa dikatakan sebagai GURU atau PANUTAN untuk memberikan contoh sikap secara lahiriah dan batiniah dalam segi Islam sehari-hari. Sebenarnya apa dan dari mana asal muasal Gelar Haji tersebut. Kita simak apa yang ada dalam artikel2 atau paparan para ahli yang patut kita renugkan sebagai berikut di bawah ini.
Haji adalah gelar homonim yang memiliki dua etimologi yang berbeda. Dalam budaya Islam Nusantara di Asia Tenggara, GELAR HAJI umumnya digunakan untuk orang yang sudah MELAKSANAKAN HAJI. Istilah ini berasal dari bahasa Arab (حاج) yang merupakan bentuk isim fail (partisip aktif) dari kata kerja 'hajj' (Arab: حج, 'pergi haji') atau dari kata benda 'hajj' (Arab: حج, 'ibadah haji') yang diberi sufiks nisbah menjadi 'hajjiy' (Arab: حجي). Arti lainnya adalah berasal dari kebudayaan Nusantara pra-Islam era Hindu-Buddha, yaitu HAJI atau AJI yang berarti "RAJA". Di beberapa negara, gelar haji dapat diwariskan turun-temurun sehingga menjadi nama keluarga seperti Hadžiosmanović dalam bahasa Bosnia yang berarti 'Bani Haji Usman' alias 'anak Haji Usman'. Di negara-negara Arab, gelar haji awam digunakan sebagai penghormatan kepada orang yang lebih tua terlepas dari pernah haji atau belum. Gelar haji juga digunakan di negara-negara KRISTEN BALKAN yang pernah dijajah Imperium Usmani (Bulgaria, Serbia, Yunani, Montenegro, Makedonia dan Romania) bagi orang KRISTEN yang sudah pernah berziarah ke Yerusalem dan Tanah Suci
Lebih Lanjut Baca Asal Gelar Haji Di Indonesia, Tekanan Belanda Atas Perhajian, Sejarah Perhajian Di Nusantara, Kafilah Haji Dunia Abad Ke-13
Wallahu a’lam bish-shawab<
“Dan Allah Mahatahu yang benar/sebenarnya”
(dihimpun dari berbagai sumber – rully hasibuan)
Langganan:
Postingan (Atom)